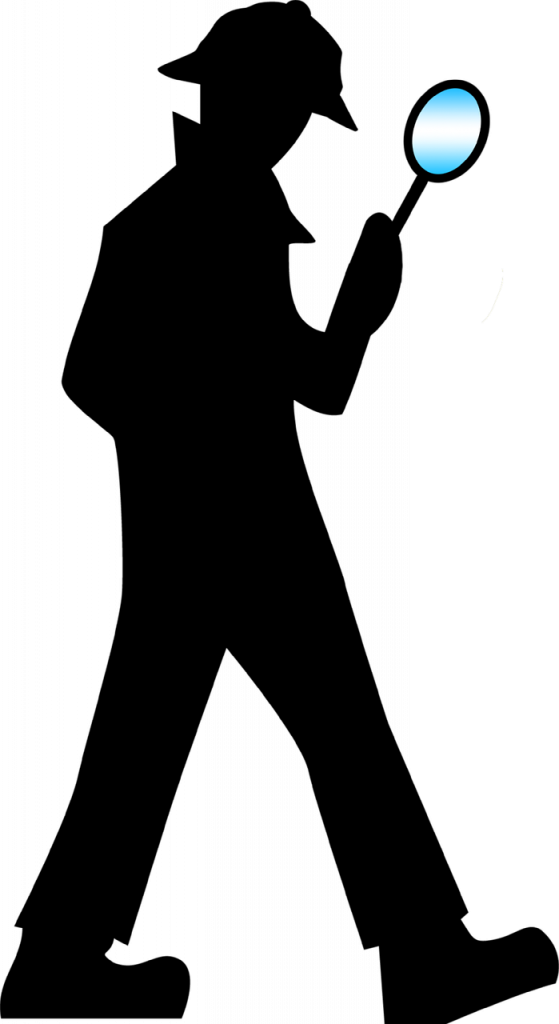Aku tidak tahu sejak kapan dia menguntitku. Perasaanku tidak tenang dibuatnya. Terus aku pantau kaca spion mobilku. Tidak ada yang aneh. Semua normal. Tidak ada yang mencurigakan. Tapi, kenapa hati ini tidak tenang? Serasa ada yang mengikutiku.
Mulutku terus komat-kamit. Lantunan istigfar tidak berhenti dari bibir ini. Berharap ini akan menenangkan hatiku. Setidaknya, sampai aku bertemu dengan seseorang yang bisa menjadi pendengar ketakutanku.
Aku sampai di parkiran kampus. Gegas aku naik ke lantai lima di mana ruang kuliahku berada. Pintu ruang kuliah terbuka. Di sana ada dia. Dia yang bisa menenangkan aku. Langkah aku percepat setengah berlari.
“Iva!!”
Iva kaget mendengar teriakanku. Aku berlari menuju kursi di sebelahnya.
“Wa`alaikumussalam,” bagiku itu teguran halus dari Iva karena aku tidak mengucapkan salam seperti biasa. Iva melihat nafasku naik-turun tidak beraturan, “kamu kenapa?”
“Aku nggak tenang,” ujarku rusuh, “Va, aku ngerasa ada yang ngikutin aku sepanjang jalan dari rumah ke sini.”
Dahi Iva berlipat, “Siapa?”
“Aku nggak tahu. Tiap aku lihat spion, nggak ada yang aneh. Nggak ada yang mencurigakan. Biasa aja.”
“Feeling?” aku manggut-manggut. Iva tersenyum, “banyakin istigfar. Malaikat maut yang menguntit kita tiap saat. Itu kali. Aku juga tiap saat dikuntit dia. Semua dari kita dikuntit dia.”
Aku pukul lengan Iva sembari cemberut, “Jangan becanda sama maut, ah!”
Iva terkekeh sambil jarinya terus menari di atas catatannya. Entah apa yang sedang dia tulis, “Siapa yang becanda? Malaikat maut selalu mengintai kita, Alifa sayang. Selalu bersiap dengan kedatangannya.”
“Jadi, maksud kamu, aku bisa ngerasain malaikat maut? Istimewa banget,” nafasku mulai teratur.
“Al, kita bisa, kok, ngerasain dia datang suatu hari nanti saat Allah hendak memanggil kita pulang ke sisi-Nya. Wallahualam.”
Bukan dia. Bukan malaikat maut yang aku rasakan. Aku harap. Tapi, mungkin benar dia yang datang mendekat. Apa aku sudah siap jika dia yang datang? Ya Allah, rasanya dosa ini masih menggunung. Belum tuntas aku meminta ampun untuk semua itu pada-Nya. Sebanyak apapun ampunanku aku merasa belum cukup untuk menghapus dosa ini. Aku harap bukan malaikat maut itu yang menjemputku. Ah, kenapa Iva kali ini tidak menenangkan aku? Kenapa malah jadi membuat aku makin kalut?
“Apa mungkin dia?” Iva menunjuk seseorang yang ada di luar kelas dengan pulpennya. Aku mengikuti arah tunjuk Iva.
Wildan. Lelaki yang mengejar cintaku sejak aku duduk di bangku kuliah sarjana. Dia di luar sana sedang berbicara dengan dosen pembimbing tesisnya. Sempat dia melirik ke arahku. Namun, dia tarik lagi. Lirikan matanya persis seperti tatapan mata terakhir kali aku menolaknya. Aku menolaknya hampir sepuluh kali. Dia tidak menyerah dengan cintanya. Aku tidak menyerah dengan penolakanku.
“Kalau kamu berani, datangi orang tua aku,” itu kataku padanya saat dia kembali menyatakan cintanya padaku.
“Al, aku nggak mau buru-buru. Aku harus cari uang dulu buat hidup kita ke depannya. Aku mau kita pengenalan dulu.”
“Pacaran?” tanyaku tegas. Wildan mengangguk, “aku nggak mau!” aku melengos pergi, Wildan menahan.
“Al, aku bener-bener cinta sama kamu.”
“Yach, buktikan! Jangan Cuma ngomong doang. Satu-satunya bukti cowok cinta sama ceweknya, Cuma satu. Lamar dan nikahi. Nggak ada cara lain.”
“Aku minta waktu sama kamu. Aku pengin kita mantap menikah. Nggak mau gerasah-gerusuh.”
Aku tidak menerima alasan apapun. Bagiku, laki-laki sejati yang mencintaiku bukanlah laki-laki yang menyuruhku untuk menunggunya dalam waktu tidak tentu. Tapi, laki-laki yang langsung dengan gentle memintaku pada orang tuaku. Bukan memintaku mengecap cintanya yang belum halal.
Aku menggelengkan kepala lagi, “Kamu pengecut! Apa mungkin aku mau bersuamikan seorang yang banyak omong, nihil tindakan? Nggak, Wil! Aku butuh laki-laki yang gentle. Talk less, do more. I marry a man, not a chicken.”
Penolakan terakhirku rasanya memang penolakan yang paling menyakitkan dan menampar Wildan. Ada sedikit sesal aku mengatakan hal tersebut. Aku tidak harus berkata sekeras itu padanya. Aku tidak tahu bagaimana perasaan Wildan saat itu. Aku hanya bisa melihat sorot matanya. Sorot mata yang tidak biasa. Tajam. Matanya seraya menantang dan mengancam. Entahlah.
“Apa mungkin dia, Va?”
Iva mengangkat bahunya, “Ah, udahlah. Jangan dipikirin. Aku tadi asal ngomong doang. Hehe.”
Pukul empat sore kelasku selesai. Aku sedang merapikan buku-bukuku ketika Iva bertanya.
“Al, malam ini kamu ngajar?” sembari menyelesaikan magisterku, aku juga mengajar di sebuah perguruan tinggi swasta.
“Bukan ngajar, tapi asistensi, sih.”
“Hati-hati, yach?”
Deg! Iya benar. Malam ini aku harus mengasistensi praktikum. Walaupun jadwal praktikum sampai jam sembilan, tidak jarang pada praktiknya sampai jam sepuluh atau lebih. Tergantung materi dan tergantung sigap praktikanku. Mengingat perasaan was-was itu belum juga sirna, aku ragu untuk kerja malam ini. Apa aku izin untuk malam ini? Aku belum pernah izin mengajar atau mengasistensi. Jadi, kali ini aku minta izin saja daripada ada hal buruk terjadi.
***
Lagi-lagi datang. Rasa itu kembali menghampiriku ketika aku keluar dari rumah. Ada yang menguntit. Aku yakin. Mataku kali ini aku pasang lebih lincah. Aku lebih sering melongok ke kaca spionku. Sering aku berhenti di pinggir jalan untuk memastikan.
Dapat!
Ada seseorang berjaket kulit dengan motor mengikutiku. Setiap aku berhenti dia ikut berhenti sepuluh meter di belakangku. Ini tidak biasa. Bukannya tenang mengetahui dugaanku benar, hati ini malah semakin ciut. Dengan kecepatan tinggi, aku menerobos jalanan. Aku seperti kerasukan. Aku ingin lepas dari pengintaiannya. Apapun alasan dia menguntit, aku ingin hilang darinya.
“Iva!” kembali aku rusuh mendatangi Iva yang baru saja mau masuk ke dalam kelas, “benar kataku. Ada yang ngikutin aku.”
“Siapa?” tanya Iva cemas.
Aku menggelengkan kepala, “Aku nggak tahu. Dia pakai jaket kulit sama helm full face. Va, nanti kamu pulang bareng aku, yach. Kamu nginep di rumah aku, please. Aku takut pulang sendiri.”
Iva mengangguk tanda setuju. Raut wajahnya ikut kalut sepertiku.
Sepulang kuliah aku putuskan untuk tidak mengajar. Aku hanya memberikan tugas makalah pada mahasiswaku. Iva pulang bersamaku. Dia akan menginap di rumahku. Selama di rumah, Iva memintaku banyak berdoa dan berdzikir untuk keselamatanku. Iva juga mencoba membantuku menerka siapa yang menguntit aku itu.
“Kamu punya musuh?” aku menggelengkan kepala, “ada orang yang kamu buat sakit hati?”
Aku diam mengingat. Satu orang yang aku ingat jelas pernah aku sakiti hanya Wildan.
“Aku nggak tahu kalau yang lain, tapi Wildan satu-satunya orang yang aku pernah sakiti sama kata-kata penolakan aku. Kalau memang itu Wildan, untuk apa dia menguntit aku? Kalau dia memang cinta sama aku, dia nggak mungkin mau nyakiti aku.”
“Wallahualam. Orang kalau udah disakiti walaupun cinta, bisa jadi berubah. Bukan maksud aku su’udzon sama Wildan, tapi waspada aja. Mending kamu minta maaf sama dia cepet-cepet. Takut dia nggak terima perlakuan kamu.”
Aku tercenung. Benar kata Iva, tidak ada salahnya aku meminta maaf pada Wildan. Ah, kalau benar dia yang menguntit aku, untuk apa?
“Selain dia?” tanya lagi Iva. Aku kembali membuka kotak memoriku. Sebisa mungkin aku mengeruk semua memori yang ada. Siapa saja yang mungkin aku sakiti.
“Dinda?” kusebut sebuah nama. Seorang kawan yang aku kenal di masa sekolah sarjana, “kadanag aku suka sinis dan dingin sama dia,” ujarku, “tapi itu karena dia orangnya nyebelin,” aku berusaha membela diri, “dia suka sok ngambil alih semua kontrol kalau lagi kerja kelompok. Makanya aku sering judes sama dia.”
Iva beranjak dari ranjang. Dia ambil secarik kertas dan pulpen dari meja belajarku. Lantas, Iva kembali ke sampingku. Dia mencatat nama orang dan apa yang telah aku lakukan pada orang-orang itu. Aku melirik catatan Iva. Tidak aku sangka banyak juga orang yang aku sakiti dengan sikapku meskipun aku merasa tidak menyakiti mereka. Tapi, deretan nama di atas kertas itu berpotensi sakit hati. Dari hal yang sepele sampai hal yang besar.
Sejenak aku lupa dengan masalah si penguntit itu. Aku baru sadar. Ini baru selembar kertas. Manusia yang mencatat. Bagaimana dengan catatanku yang ditulis oleh malaikat? Kertas mana yang banyak catatannya? Kertas kebaikanku atau keburukanku?
“Va.”
“Yach?”
“Apa kamu juga pernah aku sakiti hatinya selama ini?”
Iva menoleh padaku. Kami saling pandang dengan tatapan yang dalam. Iva sudah menjadi sahabatku sejak kami duduk di bangku SMA. Sangat mungkin dalam jangka waktu bertahun-tahun, di tengah persahabatan kami, aku menyakiti hatinya tanpa aku sadari.
“Pernah,” Deg! “sering,” aku menarik tatapan mataku darinya. Malu, “tapi,” aku melirik dengan ujung mataku, “aku udah maafin kamu, kok, tiap kamu bikin aku kesel atau sakit hati. Kamu tahu kenapa?”
Aku memutar kepalaku, “Kenapa?”
“Soalnya aku pengin kamu juga maafin aku kalau aku bikin kamu sakit hati,” ujarnya dengan sebuah senyuman di ujung kalimat.
Aku turut tersenyum, “Maafin aku, yach, Va?”
Masih dengan tersenyum, Iva berkata, “Aku nggak mau orang lain nggak maafin aku kalau aku punya salah sama mereka makanya aku maafin mereka duluan.”
Mungkin ini sebabnya persahabatan aku dan Iva bertahan hingga bertahun-tahun lamanya. Iva sahabat yang baik. Bukan karena dia selalu membenarkan sikap dan kataku, tapi dia selalu memberikan kebenaran padaku.
***
“Aku harap penguntit itu ngikutin aku hari ini.”
Iva bengong mendengar gumamanku di depan cermin saat merapikan kerudungku, “Aku nggak salah denger, Al?”
Aku menengok Iva lalu menggelengkan kepala, “Nggak! Aku bakal menemui dia dan tanya apa mau dia.”
“Al, kalau dia orang jahat gimana?”
“Bismillah aja, Va.”
Air mukaku tampak tenang terpantul di cermin itu, berbeda dengan Iva. Kini wajahnya yang rusuh tidak karuan gara-gara mendengar tekadku yang gila. Entah kekuatan dan keyakinan dari mana aku mengatakan itu semua. Namun, yang aku tahu aku tidak mau lagi dirundung ketakutan. Semua ini harus dihentikan. Jika memang ternyata akhirnya malaikat maut yang menemuiku seperti apa kata Iva, aku… aku siap. Bismillah.
Aku bawa mobil keluar dari garasi. Iva duduk di sampingku.
“Al, kalau emang penguntit itu ngikutin kamu lagi, mending kamu lapor polisi aja. Kamu giring dia ke kantor polisi.”
“Dia bakal ngelak, Va. Dia pasti kabur. Aku harus hadapi.”
“Al, jangan gila dong!”
Aku tidak menghiraukan kecemasan Iva. Kami berangkat ke kampus. Mataku sesekali melihat ke spion. Berharap lelaki berjaket kulit itu muncul. Iva diam seribu bahasa di sampingku. Aku lihat mulutnya bergerak tanpa suara. Sepertinya, dia sedang berdoa. Aku kembali melihat spion. Belum ada tanda-tanda kehadiran sang penguntit. Apa dia akan muncul?
Yap! Dia muncul. Muncul di antara mobil-mobil di belakangku.
“Itu dia!” seruku.
Iva balik badan. Wajahnya mendadak pucat pasi, “Al, ke kantor polisi aja, yuk!”
Aku tidak menggubris. Aku sibuk memainkan gigi, setir, rem, kopling, dan gasku. Aku menancap gas menerobos kerumunan mobil di jalanan kota. Iva memejamkan mata dengan mulut sibuk berdoa.
Satu, dua, tiga, empat mobil aku salip dengan cepat. Si penguntit berjaket kulit lihai mengikutiku. Aku belok, dia ikut belok. Aku menukik, dia ikut menukik. Sebuah perumahan ada di depan. Aku belokkan mobil masuk ke perumahan itu. Dia mengikuti. Aku injak rem cepat. Ligat aku lepas sabuk pengaman dan membuka pintu.
“Al, jangan!” Iva menarik lenganku, tapi aku tepis.
Aku lihat pria berjaket kulit itu menghentikan motornya di belakang mobilku.
“Kamu siapa?!” teriakku sengaja. Aku harap teriakanku bisa mengusik warga perumahan tersebut kalau-kalau terjadi sesuatu nantinya, “kenapa kamu ngikutin aku?!” Iva keluar dari mobil. Di tangannya sudah dipegang telepon genggam. Sepertinya dia bersiap menelepon polisi jika ada hal buruk terjadi.
Sok gagah aku mendekat pada sang penguntit.
Laki-laki itu turun dari motornya. Dia lepas helm full face-nya. Jantungku berdegup kencang. Bayang berbagai kemungkinan terburuk berlarian di benakku. Seorang laki-laki paruh baya dengan wajah tegas dengan kumis lebat. Aku sama sekali tidak mengenalnya.
“Siapa kamu?!” seruku lagi, “apa mau kamu?!” kami berdua sempat beradu pandang. Matanya menatapku seperti elang menatap mangsanya.
“Nama saya Hakim,” ujar laki-laki itu, “saya ngikutin mbak soalnya mau tanya itu,” dia menunjuk mobilku, “itu sekolah yang bikin obat itu, kan?”
Keningku mengernyit. Perlahan aku memutar kepalaku ke arah mobilku. Di jendela belakang mobilku tertempel stiker nama dan lambang kampus di mana aku mengajar. Iva berjalan ke belakang mobilku dan melihat apa yang ditunjuk laki-laki tua itu. Aku menoleh kembali pada si penguntit.
“Maksud bapak apa?” tanyaku dengan nada bicara yang rendah.
“Saya pengin daftarin anak saya sekolah ke sekolah bikin obat itu, tapi karena saya perantau saya nggak tahu nama jalan di kota ini. Makanya saya ngikutin mbak. Saya pengin tanya sama mbak soal sekolah itu.”
“Hah?! Cuma itu, Pak?!” bapak itu mengangguk. Wajahnya ketika bicara tidak seseram saat dia diam, “serius, Pak, Cuma pengin tanya itu?!” bapak itu manggut-manggut yakin sembari menyeringai.
Badanku lemas mendengar itu semua. Aku dikuntit selama tiga hari hanya karena seorang perantau yang penasaran dengan alamat perguruan tinggi di mana aku mengajar. Aku ketakutan karena seorang bapak yang gigih ingin menyekolahkan anaknya di tempatku. Aku menoleh pada Iva yang sedari tadi sudah aku buat sport jantung gara-gara aksi kejar-kejaran ala film Hollywood. Dia bersandar lemas ke mobilku.
Oleh: Revika Rachmaniar
sumber gambar : https://pixabay.com/en/detective-magnifying-glass-man-1299558/